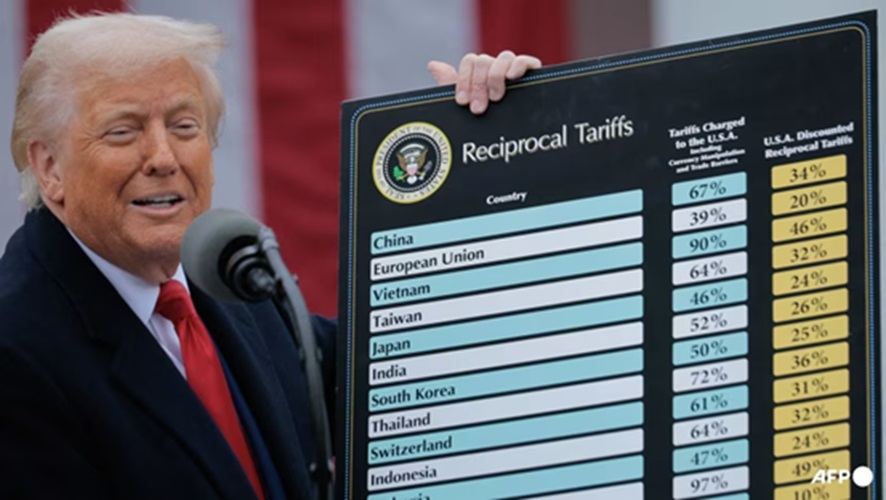Aktivis Korsel Akhiri Gaya Hidup Konsumtif dengan Setop Beli Baju Baru
- Adaptasi Iklim
Tadinya Lee So-yeon, seorang shopaholic asal Korea Selatan (Korsel) yang kini menjadi aktivis iklim, terbiasa membeli pakaian baru hampir setiap hari hingga sebuah mantel musim dingin seharga 1,50 dollar AS memicu kesadaran yang membuatnya berhenti berbelanja sama sekali.

Ket. Aktivis iklim Korsel, Lee So-yeon, sedang menyeleksi pakaian yang ia terima dari rekan dan keluarganya dari lemari bajunya beberapa waktu lalu. Menyadari bahwa industri mode global merupakan salah satu industri yang paling berpolusi
Doc: AFP/ANTHONY WALLACESaat melihat jaket berlapis yang sangat murah di toko H&M di Amerika Serikat (AS), tempat ia bekerja saat itu, Lee bertanya pada dirinya sendiri bagaimana mungkin satu potong pakaian bisa dijual dengan harga semurah itu.
Perempuan berusia 30 tahun itu kemudian menyelami lebih dalam metode produksi tren pakaian terkini dan merasa ngeri melihat dampak negatif hiperkonsumerisme terhadap manusia, sosial, dan lingkungan di planet ini serta terhadap kesehatan mental perempuan yang membuat dan membeli pakaian murah.
"Saya dulu terbiasa membeli satu pakaian baru setiap hari (kerja) dalam sepekan," aku Lee kepada AFP, seraya menambahkan bahwa setiap barang dari pengecer besar di jalan raya biasanya harganya kurang dari satu dollar saja.
Namun, Lee mengetahui bahwa alasan mengapa pakaian itu sangat murah adalah karena perempuan yang menjahit untuk perusahaan dibayar murah, sementara model bisnis itu sendiri menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan.
Akibatnya Lee berhenti membeli pakaian baru dan bahkan ia tak membeli satu pun pakaian tren terbaru sejak mendapat pencerahan sekitar enam tahun lalu.
Sebelumnya lemari pakaiannya amat padat terdiri dari barang-barang bekas yang ia terima dari teman-teman dan keluarga, termasuk jaket kulit antik yang dulunya milik ibunya.
Anda mungkin tertarik:
Tidak seperti barang-barang tren terkini yang sering kali dirancang untuk dibuang setelah beberapa kali dipakai, setiap potong pakaiannya tidak dapat tergantikan karena memiliki cerita dan sejarah yang unik, kata dia.
"Pada akhirnya, pakaian yang paling ramah lingkungan adalah pakaian yang bertahan di lemari pakaian kita," ungkap Lee.
Memutus Siklus
Lee kini mengorganisasikan kegiatan barter pakaian dengan teman-temannya dan keluarga, dan telah menulis buku untuk mempromosikan gagasan menghargai pakaian berdasarkan "kisah di baliknya," alih-alih mengejar tren yang bersifat sementara.
Kini Lee adalah bagian dari gerakan global yang kecil tetapi berkembang yang berupaya mempromosikan pakaian bekas dan membantu orang-orang, khususnya kaum perempuan, untuk keluar dari siklus konsumsi berlebihan.
Salah satu aplikasi barter pakaian yaitu Lucky Sweater, platform fokus bagi pengguna untuk saling bertukar barang dari lemari mereka, dengan menekankan pada merek yang berkelanjutan, kata pendirinya, Tanya Dastyar, kepada AFP.
"Kita tadinya diprogram untuk percaya bahwa satu-satunya cara untuk mengekspresikan gaya busana saya atau menunjukkan bahwa saya cantik atau trendi adalah dengan pakaian baru. Namun ternyata Anda tetap bisa tampil modis, merasa baik, dan tampil hebat tanpa harus melakukan itu," kata Dastyar, seraya menambahkan bahwa meskipun berdagang pakaian tidak memberikan dampak dopamin yang sama cepatnya seperti membeli barang mode cepat, hal itu jauh lebih menguntungkan seiring berjalannya waktu.
Meningkatnya penggunaan aplikasi tersebut menunjukkan orang-orang ingin mengubah hubungan mereka dengan pakaian dan konsumerisme, kata dia.
Orang-orang sepertinya menyadari: "Saya tidak harus mengikuti tren dan saya bisa berpakaian dengan cara yang membuat saya nyaman," kata Dastyar.
Sementara bagi Lee, memutus siklus konsumsi pakaian murah membantunya meningkatkan kesehatan mentalnya. Saat remaja, ia akan khawatir tentang apa yang akan dikenakan pada perjalanan sekolah saat seragam tidak diwajibkan, setidaknya sebulan sebelumnya dan akan pergi berbelanja untuk meredakan ketakutannya.
Namun ketika ia mengetahui tragedi Rana Plaza di Bangladesh tahun 2013 yang merupakan salah satu bencana industri terburuk di dunia yang menewaskan lebih dari 1.130 pekerja pabrik garmen, kebanyakan dari mereka adalah perempuan muda, peristiwa itu menjadi titik balik baginya.
“Para pekerja pabrik itu ternyata tewas saat membuat pakaian untuk perempuan seperti saya," ucap Lee.
Bank Dunia memperkirakan industri mode global merupakan salah satu industri yang paling berpolusi, menyumbang hingga 10 persen emisi gas rumah kaca. Sebagian besar pakaian modern terbuat dari bahan sintetis seperti nilon dan poliester, yang pada dasarnya adalah plastik dan tidak terurai secara hayati di tempat pembuangan sampah, menurut data industri.
Mengupayakan pakaian agar tidak berakhir di tempat pembuangan sampah dapat membantu, tetapi di Korsel masih banyak yang enggan menggunakan pakaian bekas, kata Kim Dong-hyun, yang mengelola pabrik ekspor pakaian bekas.
"Orang-orang sering kali tidak menyukai seseorang yang mengenakan pakaian bekas karena pakaian tersebut dianggap sebagai barang yang tidak diinginkan," tutur Kim. AFP/I-1