
Satu Tahun Invasi, Rusia Tak Berhenti Menyerang, Ukraina Tak Berhenti Bertahan

Kota di Ukraina yang hancur akibat perang dengan Rusia.
Radityo Dharmaputra, Universitas Airlangga
Tepat satu tahun sudah konflik senjata antara Rusia dan Ukraina berlangsung. Ribuan warga sipil, termasuk anak-anak, meninggal dunia dan terluka akibat invasi Rusia ke Ukraina tersebut.
Perang juga telah menyebabkan krisis kemanusiaan, krisis energi yang menyebabkan sulitnya akses air bersih dan listrik, dan pembunuhan massal di banyak kota di Ukraina.
Dalam pidato tahunannya di Moskow pada 21 Februari 2023, di hadapan parlemen (Federal Assembly) dan perwakilan militer Rusia, Presiden Rusia Vladimir Putin justru semakin menunjukkan niatannya mengeskalasi konflik. Ia menegaskan kembali bahwa wilayah Ukraina secara historis adalah bagian dari teritori Rusia, disertai pernyataan bahwa Rusia menunda keikutsertaannya dalam perjanjian kontrol nuklir dengan Amerika Serikat (AS).
Di saat yang sama, Presiden AS, Joe Biden, mengunjungi Kyiv untuk bertemu dengan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, guna menekankan bahwa AS mendukung penuh kedaulatan Ukraina.
Prospek perdamaian di antara keduanya tampak masih cukup jauh dari harapan.
Banyak pihak mendesak Rusia dan Ukraina untuk segera menghentikan konflik, serta agar pihak ketiga seperti AS tidak memberikan bantuan senjata, terutama bagi Ukraina, karena akan memperkeruh konflik.
Padahal tidak semudah itu. Jika kita memahami penyebab dan konteks sejarah invasi Rusia ke Ukraina serta perkembangan situasi domestik masing-masing negara, kita akan bisa melihat mengapa keduanya sama-sama tidak akan mudah berhenti berperang, paling tidak selama satu tahun ke depan.
Rusia Tidak Mungkin Berhenti Menginvasi
Sejak awal, invasi ini memang bukan disebabkan oleh kompetisi Rusia dengan Barat. Konflik ini juga bukan karena Putin merasa terancam oleh potensi perluasan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dengan langkah Ukraina yang mendaftar jadi anggota aliansi militer terbesar di Eropa tersebut.
Setidaknya ada tiga hal yang perlu kita pahami mengenai konteks sejarah hubungan Rusia dengan negara-negara bekas Uni Soviet.
1. Rusia masih meyakini bahwa Ukraina adalah wilayahnya
Rusia, sebagaimana yang Putin katakan berulang kali, menganggap bahwa Ukraina adalah bagian historis dari wilayah Rusia. Oleh karenanya, Ukraina harus menjadi area di bawah pengaruh dan kekuasaan Rusia.
Untuk itu, apapun yang NATO maupun Ukraina lakukan untuk mengurangi tensi di kawasan tersebut tidak akan diterima oleh Rusia, selama hal itu masih mengurangi pengaruh Rusia di kawasan Eropa Timur.
Rusia hanya ingin mempertahankan kontrol mereka terhadap wilayah yang menjadi hak kuasa mereka dan tidak akan berhenti sebelum ada kepastian bahwa kekuasaan ini tetap terjaga.
2. Reputasi Putin dipertaruhkan
Kita juga perlu mencatat kondisi domestik Rusia sebelum melakukan invasi ini.
Demonstrasi besar pada akhir tahun 2021 oleh para pendukung pemimpin oposisi Alexey Navalny, telah mengindikasikan mulai turunnya popularitas Putin dan tidak stabilnya rezim pemerintahannya.
Pengalihan isu domestik dengan cara menyerang Ukraina sudah menjadi pola umum kebijakan Rusia.
Pada 2013-2014, untuk mengalihkan isu yang bisa mengganggu reputasinya dan menguatkan rezim, Putin memulai invasi ke wilayah Ukraina. Namun, saat itu invasinya dilakukan secara selektif di Krimea dan secara tersembunyi di Donbas. Kemudian tahun 2022, invasi dilakukan secara masif di hampir seluruh wilayah Ukraina.
Pencaplokan wilayah Ukraina oleh Rusia, baik pada 2014 maupun 2022, telah membuat popularitas Putin langsung meningkat di dalam negeri.
Maka dari itu, tidak ada keuntungan bagi Putin untuk berhenti menyerang.
Sebaliknya, jika menghentikan invasi, artinya Rusia mengakui kekalahannya melawan negara yang jauh lebih kecil. Ini akan menjatuhkan, bahkan menghilangkan, reputasi Putin sebagai pemimpin besar yang kuat. Dan jika ini terjadi, akan ada konflik internal di antara elit politik Rusia, apalagi menjelang pemilihan umum (pemilu) Rusia pada tahun 2024.
3. Pantang mundur karena sudah habiskan modal besar
Ketidakmampuan Rusia menaklukkan seluruh wilayah Ukraina dalam waktu singkat tidak serta merta membuat Putin mengerahkan seluruh tentara Rusia dan memobilisasi massal warga sipil. Ia tetap bersikukuh memakai istilah "operasi militer khusus" dan mobilisasi parsial. Dengan begitu, Putin masih bisa meyakinkan rakyatnya bahwa invasi ini bukan perang terbuka.
Putin melakukannya karena memahami bahwa masyarakat Rusia masih cukup trauma dengan Perang Dunia II. Mobilisasi parsial saja sudah menimbulkan gejolak penolakan dan membuat sejumlah besar warga Rusia pergi ke luar negeri.
Resistensi yang mulai muncul di dalam negeri kemudian direspons dengan represi yang begitu keras oleh pemerintah, termasuk membredel media-media independen dan melarang penggunaan istilah "perang".
Langkah-langkah Putin tersebut telah mengorbankan banyak hal, baik secara ekonomi maupun modal politik domestik dan kepercayaan masyarakat. Kalau sampai gagal, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Putin akan menurun, dan itu akan mengancam keberlanjutan rezimnya.
Ukraina Tidak Akan Berhenti Bertahan
Setelah memahami kondisi internal Rusia, kita perlu memahami bahwa Ukraina punya hak untuk mempertahankan dirinya dari serangan negara lain.
Posisi Zelenskyy juga sangat sulit. Tekanan dari negara-negara lain agar Rusia-Ukraina mencari jalan damai biasanya berujung pada dua hal: (1) mengakomodasi kepentingan Rusia, terutama dalam konteks konsesi teritorial dan keberadaan etnis dan penutur bahasa Rusia di Ukraina, serta (2) prospek bergabungnya Ukraina ke Uni Eropa dan NATO.
Masalahnya, meskipun Zelenskyy bisa saja mempertimbangkan aspek strategis dari kedua hal tersebut, sebagian besar masyarakat Ukraina satu suara menolak konsesi apa pun pada Rusia. Apabila Zelenskyy bertindak sendiri, tentu legitimasinya sebagai pemimpin akan hilang.
Terlebih lagi, masyarakat Ukraina sudah mengalami penderitaan selama satu tahun terakhir, sehingga tidak akan mau berurusan dengan penjajah dan penyerangnya. Dalam konteks ini, saya pribadi menganalogikan langkah memaksakan perdamaian maupun rekonsiliasi ini bagaikan memaksa korban perkosaan untuk berdamai dengan pemerkosanya.
Kita, sebagai pihak yang tidak merasakan penderitaan masyarakat Ukraina, sebaiknya tidak meminta mereka untuk berkorban lebih jauh lagi.
Dalam 10 poin tawaran perdamaian yang disampaikan secara virtual oleh Zelenskyy dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada November lalu, terlihat jelas bahwa Ukraina baru akan bernegosiasi apabila Rusia berhenti melakukan agresi dan "pulang" ke wilayah mereka sendiri.
Namun, kembali lagi, Rusia tidak akan "pulang" karena alasan yang sudah disebutkan di atas.
Ini juga menjadi alasan mengapa negara-negara Barat terus menyokong Ukraina dengan senjata tambahan. Mereka bisa melihat bahwa tidak ada peluang Putin akan berhenti, kecuali pasukan Rusia benar-benar dikalahkan di medan pertempuran. Pada saat yang sama, negara-negara seperti Iran dan Cina juga masih memberikan dukungan politik bagi Rusia.
Di tengah situasi seperti ini, sangat sulit bagi negara lain untuk mendorong perdamaian bagi Rusia dan Ukraina.
Apa yang Bisa Dilakukan Negara Lain, termasuk Indonesia?
Ada dua opsi yang bisa dilakukan saat ini:
Pertama, membiarkan dulu eskalasi konflik sampai titik "matang" (ripeness).
Dalam kajian tentang negosiasi perdamaian, ada konsep yang disebut "mutually hurting stalemate". Ini adalah kondisi ketika kedua belah pihak berada di posisi impas, keduanya sama-sama tidak bisa maju lagi, kecuali dengan harga yang sangat tinggi.
Contoh harga tinggi adalah potensi perang nuklir. Meski akan menghancurkan sebagian wilayah Ukraina, konflik semacam ini juga akan memicu respons nuklir dari negara-negara seperti AS dan Uni Eropa.
Ketika ada di posisi "matang untuk berdamai" inilah baru pihak ketiga bisa menawarkan untuk menjadi mediator. Namun, tentu resiko dari pembiaran ini adalah meningkatnya jumlah korban, terutama dari pihak Ukraina.
Kedua, menggalang bantuan dari negara-negara kekuatan menengah - terutama negara Global South (dari kawasan Afrika, Asia, dan Amerika Latin) - untuk menekan Rusia secara langsung agar menghentikan dulu serangannya serta meninggalkan wilayah yang mereka caplok sejak 24 Februari tahun lalu.
Selama ini, tekanan hanya dilakukan melalui forum formal PBB maupun G20 dan dengan bahasa yang diplomatis. Tekanan langsung ini bisa berupa pernyataan sikap bersama dari negara-negara kekuatan menengah, termasuk Indonesia, dan mengirim delegasi bersama ke Rusia.
Sesudah itu, negara-negara tersebut bisa menawarkan forum perdamaian yang diselenggarakan di wilayah netral, untuk membahas soal jaminan keamanan bagi Ukraina, NATO, Donbas, dan isu sensitif lainnya.
Ini juga bisa menjadi momentum bagi negara kekuatan menengah untuk mengambil peran utama sekaligus memastikan bahwa perundingan tidak hanya menjadi ajang kontestasi negara-negara besar seperti AS, Uni Eropa, Rusia, dan Cina, tapi juga mengakomodasi persepsi negara lain.![]()
Radityo Dharmaputra, Lecturer in Russian and Eastern European Studies, Department of International Relations, Universitas Airlangga, Universitas Airlangga
Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.
Redaktur : -

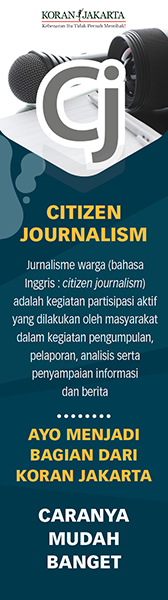

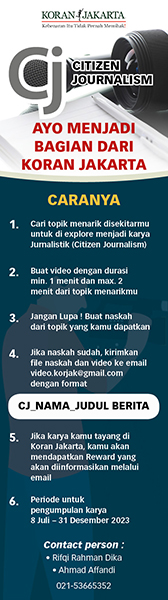
Komentar
()Muat lainnya