
Saracen, Anomali Berdemokrasi

Oleh Ach Fadil
Terbongkar dan mencuatnya kasus sindikat Saracen beberapa waktu lalu, tak lebih sebagai anomali dalam demokrasi. Ini suatu penyimpangan karena tidak sejalan dengan ritme keadaban sebagai harapan dari sistem yang cikal-bakalnya berasal dari Yunani tersebut.
Menurut aparat kepolisian, dari sindikat Saracen itu, bahasa-bahasa beraroma hate speech, intoleransi, rasialisme, sektarianisme, dan bahkan dusta atau hoaks (hoax) dimunculkan sebagai komoditas yang dikelola secara terorganisir, sistematis, dan masif. Ini diorkestrasikan di jejaring media sosial, utamanya Facebook.
Saracen sebagai produk hoaks, alih-alih dianggap sebagai alarm berbahaya bagi negeri, seorang akademikus, Rocky Gerung, melalui mimbar Indonesia Lawyers Club (ILC) TVOne yang mengangkat tema Halal-Haram Saracen belum lama ini, justru menganggap hoaks sebagai sesuatu yang seolah "absah". Persisnya, hoaks, menurut Rocky, harus dibaca sebagai gejala penyeimbang (balancing) atas dominasi dan determinasi informasi dari pemerintah.
Untuk memperkuat argumentasinya, Rocky menyitir kisah Alan Sokal, seorang saintis bidang fisika di New York University. Dia bereksperimen dengan sengaja membuat makalah hoaks "ilmiah" dan dimuat di jurnal studi budaya Social Text pada tahun 1996.
Makalah itu pada dasarnya dimaksudkan untuk mengkritik dan membuktikan bahwa kebanyakan orang mudah menerima informasi saja, tanpa ada kesediaan terlebih dulu untuk memeriksa bukti-bukti konkret, metodologi dipakai, dan seterusnya. Singkat kata, Sokal berhasil membuktikan hal itu.
Tetapi, ketika Rocky mengangkat kasus Sokal itu sebagai titik berpijak argumentasinya untuk membaca hoaks yang terjadi di Indonesia, di jagat maya, justru kehilangan relevansinya. Apalagi Rocky menganggap hoaks sebagai gejala balancing atas informasi penguasa: pihak yang dianggapnya powerful dalam memproduksi informasi.
Cara pandang seperti itu tentu saja tidak relevan. Karena pada terma balancing sendiri, konotasinya sangat positif. Sementara itu, hoaks yang terjadi di negeri ini menunjukkan gejala sebaliknya. Jika pun dianggap sebagai bentuk kritik, tidak tepat juga. Sebab yang terjadi pada hoaks negeri ini sebenarnya jauh dari kritik sebagaimana dimaksudkan Sokal. Dia hanya mengumbar retorika-retorika caci-maki, fitnah, dusta, dan permusuhan, dengan provokasi sentimen primordialitas.
Bila melihat praktik hoaks sebagaimana terjadi pada Saracen, temuan kepolisian sangat mengejutkan. Hoaks tidak hadir tanpa tujuan. Ia sengaja dihadirkan dengan motif-motif tertentu, utamanya politik dan ekonomi. Buktinya, polisi mengungkap bahwa para sindikat Saracen membuat proposal yang diajukan kepada pemesan dengan tarif 75 juta (bahkan 100 juta) untuk satu konten pesanan saja.
Artinya, hoaks memang diproduksi dengan sengaja dan sesadar-sadarnya oleh mereka yang terdidik (bisa saja para akademisi). Belum lama ini, penulis buku-buku filsafat, Ioanes Rakhmat, dalam akun Twitter-nya, @ioanesrakhmat, menyebut kaum terdidik seperti itu sebagai Junk Academicians (akademisi sampah). "Siapa paling powerful membuat hoax? Bukan negara. Karena eksekutif negara dikontrol hukum dan rakyat. Tapi para Junk Academicians. Who are they?" tulisnya.
Karena itu, sebaiknya hoaks di negeri ini dibaca sebagai anomali dalam demokrasi yang sudah sedemikian berbahaya karena bisa memperkeruh situasi dan kondisi masyarakat yang sedang tenteram. Kasus Sokal semakin membuktikan bahaya semacam itu. Karena hanya sedikit orang yang memilih menggunakan akal sehatnya untuk menelaah terlebih dulu teks berita yang muncul. Kebanyakan orang telah tertipu karena menelannya mentah-mentah.
Bahaya itu semakin nyata ketika melihat hoaks yang semakin mendapat ruang ekshibisinya di media sosial. Hanya dengan sekali klik, dalam sekejap hoaks itu bisa dikonsumsi ribuan, bahkan jutaan orang dengan spatio-temporal berbeda. Inilah yang terjadi di negeri kita.
Retorika-retorika yang dikemukakan Rocky mengenai hoaks, implikasinya bisa sangat mengkhawatirkan. Karena akan menjadi legitimasi atas sesuatu yang oleh Hannah Arendt disebut sebagai banality of evil: suatu tindakan kejahatan di mana para pelakunya menganggap absah, biasa, wajar dan lumrah karena berlangsung di bawah situasi dan kondisi yang menganggapnya demikian.
Para sindikatnya, tidak akan menyadari bahwa yang mereka informasikan berupa dusta, hasutan, dan adu domba. Sebab mereka sudah terbiasanya melakukan aktivitas tidak terpuji tersebut. Para pelakunya, selalu mempunyai dalih untuk membenarkan perbuatannya.
Pernyataan "apa yang saya posting hanya kritik" dari Sri Rahayu Ningsih (salah satu sindikat Saracen), tidak akan muncul bila dia tidak jatuh dalam selubung banalitas kejahatan itu. Maka bagaimanapun juga, mencegah semua orang agar tidak terlempar ke dalam selubung banalitas kejahatan berbasis digital itu adalah bentuk kerja merawat iklim demokrasi agar tetap kondusif. Demokrasi memang menghendaki kebebasan berpendapat, tetapi juga menolak pendapat dan perilaku destruktif.
Garis
Di dalam demokrasi, kebebasan berpendapat memang sangat dijamin, tetapi ada garis demarkasi yang harus diperhatikan. Garis demarkasi itu ketika tidak mengusik orang lain, apalagi berupa hoaks yang menyerang kepribadian atau martabat seseorang.
Dalam konteks itu, maka pemerintah dan aparat penegak hukum perlu mengambil langkah-langkah solutif serta antisipatif. Tepatlah kiranya bila pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sampai Agustus 2017 telah memblokir hampir 6.000 situs dan account yang menjadi sumber tersebar-luasnya berita-berita berisi ujaran kebencian, fitnah, dan hoaks.
Langkah antisipatif pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menekan laju persebaran hoaks mesti dipahami sebagai upaya untuk menyadarkan masyarakat akan batas kebebasan berekspresi dan seharusnya mengelola informasi. Kebijakan-kebijakan seperti itu jangan dipandang secara naif sebagai cara "dingin" pemerintah untuk membungkam kebebasan berpendapat, apalagi hanya untuk melemahkan oposisi.
Selain itu, langkah tersebut mesti dilihat sebagai upaya untuk meminimalisir kejahatan di jagat virtual. Kata "meminimalisir" sengaja digunakan karena untuk menghilangkan hoaks sama sekali utopia. Ini sama utopisnya dengan cerita dalam novel Altneuland (1902) karya Theodor Herzl yang berisi imajinasi tentang munculnya "masyarakat baru" yang hidup dalam suasana surgawi: surplus kebaikan dan defisit keburukan (kejahatan).
Bagi konsumen informasi, salah satu cara untuk menekan persebaran hoaks, tentu saja dengan chek dan rechek. Tetapi cara ini tidak akan solutif, bila konsumen tidak mengambil "jarak pandang" atas teks pemberitaan yang dibaca. Utamanya, di tengah-tengah badai politik identitas yang menjelma melalui narasi ke-kami-an versus ke-mereka-an.
Pada kondisi yang demikian, biasanya cara pandang seseorang atas sesuatu menjadi kabur, tidak bisa membedakan informasi sah dan hoaks. Sejauh teks berita yang dibaca mendukung narasi ke-kami-an, tanpa pikir panjang langsung disebarluaskan. Jarak pandang akan membantu menjernihkan.
Penulis Alumnus Universitas Paramadina Jakarta

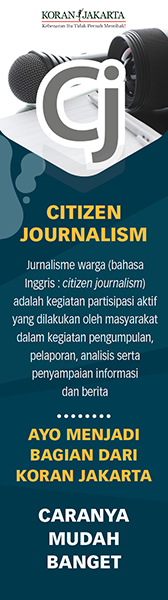

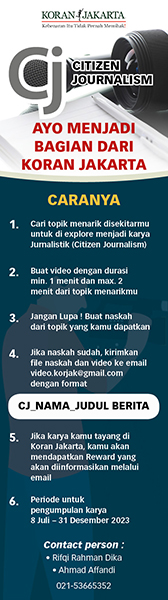
Komentar
()Muat lainnya