
NIK sebagai Basis Pajak Cederai Rasa Keadilan

GEDUNG KEMENKEU
» Orang kecil disuruh bayar pajak, sementara satu orang perampok BLBI yang rugikan negara 179 triliun rupiah tidak ditagih.
» Keadilannya di mana? Kalau nagih mulai dari yang besar, disebutkan saja siapa oknum yang punya tagihan jumbo itu, biar transparan.
JAKARTA - Kebijakan pemerintah memperluas basis wajib pajak dengan memberlakukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dinilai tidak adil. Sebab, semakin banyak rakyat kecil yang akan membayar kewajibannya ke negara, tetapi peruntukan dari pajak tersebut di antaranya untuk menyubsidi para konglomerat yang hingga kini masih mengemplang dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Brawijaya Malang, Imam Hanafi, mengatakan pemerintah wajib memfasilitasi, bukan malah membebani masyarakat. "Negara harus menyebarkan keadilan melalui instrumen kebijakan keuangan. Perlu dilakukan kajian mengapa sistem keuangan, termasuk perpajakan, belum menyejahterakan masyarakat," kata Imam.
Mengenai rencana memberlakukan NIK sekaligus sebagai NPWP, dia mengatakan hal itu tidak adil jika hanya difungsikan untuk menarik pajak, namun harus juga sekaligus jadi "big data" yang berfungsi untuk berbagai keperluan termasuk sistem keuangan, jaminan sosial, keamanan bahkan lisensi. "Jadi bukan hanya pembebanan atau kewajiban rakyat kepada negara, melainkan pula kewajiban negara kepada rakyat," kata Imam.
Dihubungi terpisah, Pengamat Ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Acmad Ma'ruf, mengatakan dengan NIK sekaligus jadi NPWP, maka konsekuensinya semua masyarakat akan dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 persen, termasuk pedagang kecil.
Begitu pula bagi masyarakat yang penghasilannya di atas ketentuan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), otomatis akan menjadi wajib pajak. "Mereka, orang kecil disuruh bayar pajak, di sisi lain ada perampok BLBI, hanya satu orang saja senilai 179 triliun rupiah tidak ditagih. Keadilannya di mana? Apakah rakyat jelata bisa menerima kebijakan seperti itu? Apalagi pajak ini digunakan untuk menyubsidi orang kaya yang mengemplang uang negara. Ini baru di satu bank swasta saja, belum utangnya di bank lain, termasuk di bank BUMN," kata Ma'ruf.
Sebab itu, dia meminta agar Menteri Keuangan menjelaskan pada publik mengapa debitor terbesar BLBI itu tidak ditagih, sedangkan masyarakat kecil malah ditarik pajak dan digunakan untuk membayar bunga obligasi rekapitalisasi ke para pengemplang utang tersebut.
"Pengemplang BLBI yang sampai saat ini belum ditagih ini adalah kejahatan ekonomi terbesar dalam sejarah bangsa ini. Satgas BLBI harus berani menagih mereka-mereka itu karena semuanya tidak ada yang kooperatif. Kalau kooperatif, dari dulu sudah menyelesaikan utangnya," kata Ma'ruf.
Dia pun meminta Satgas seperti diminta Menko Polhukam, Mahfud MD, agar mengejar pengemplang terbesar. Jangan seolah-olah dilindungi dengan dalil menunjukkan iktikad yang baik, padahal nyatanya dari dulu tidak. Bahkan, hingga hari ini belum ada satu pun yang sudah membayar lunas utangnya.
"Kalau nagih mulai dari yang besar, disebutkan saja siapa oknum yang punya tagihan jumbo itu, biar transparan. Kalau buronan lain saja langsung diumumkan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO), dibuat sangat jelas, tetapi kalau BLBI yang nilainya ratusan triliun rupiah diupayakan tidak kelihatan. Seharusnya dibuat lebih terang lagi," kata Maruf.
Pemburu Rente
Sementara itu, Manajer Riset Seknas Fitra, Badiul Hadi, mengatakan selain mengemplang BLBI dalam jumlah jumbo, oknum konglomerat itu juga disinyalir sebagai pemburu rente dengan banyak mengimpor berbagai kebutuhan pokok seperti kedelai dan gandum.
"Rakyat dicekoki untuk beralih makan mi instan, padahal bahan bakunya dari gandum yang harus diimpor dari luar negeri. Porang dan Mocaf itu baik sekali. Rakyat sangat antusias mau menanam porang, tapi tidak ada tempat yang menampung, mereka kesulitan menjual. Bagaimana mereka mau menanam? tanya Badiul.
Sebab itu, pemerintah harus melakukan adendum pada UU Cipta Kerja dengan mewajibkan setiap importir yang mengimpor barang atau jasa untuk satu dollar, harus menggunakan satu dollar devisanya yang disimpan di luar negeri. Kalau tidak mau, mereka terpaksa membeli porang dan mocaf pakai rupiah.
Program Food Estate yang digagas Presiden dan sudah ditugaskan kepada Menteri Pertahanan pada tahun lalu seharusnya dilaksanakan dengan serius. Dengan menanam singkong besar-besaran akan mampu memproduksi Mocaf sebagai pengganti terigu.
"Program Pak Prabowo (Menhan) dan Pak Trenggono (sekarang Menteri Kelautan dan Perikanan) membangun Food Estate harus didukung 100 persen, supaya jangan impor terigu lagi," katanya.
Ketidakadilan seperti itu, tambah Badiul, yang harus pemerintah perangi. Masyarakat dipaksa bayar pajak, tapi pengemplang utang negara tidak ditagih. Begitu pula impor terigu tarif bea masuknya nol persen, karena dilakukan oleh oknum konglomerat, tetapi kalau menjual porang malah dikenakan PPN 11 persen.
"Kebijakan seperti itu yang tidak masuk akal dan harus segera dibenahi," tutup Badiul.
Redaktur : Vitto Budi

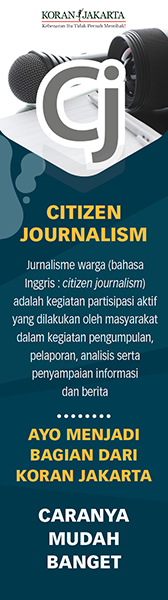

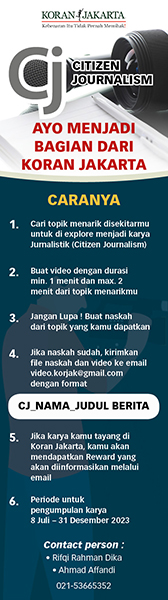
Komentar
()Muat lainnya