
Lasem, Titik Awal Pendaratan Bangsa Tiongkok di Jawa

Kota Kecamatan Lasem merupakan salah satu titik kontak pertama Jawa dengan Tiongkok, dengan berlabuhnya kapal Laksamana Cheng Ho. Tempat ini sempat menjadi pemukiman masyarakat Tionghoa dibuktikan dengan banyaknya bangunan bersejarah yang ada.
Dalam buku Lasem Kota Tiongkok Kecil karya M Azis, disebutkan bahwa Lasem di Rembang sebagai La Petite Chine (bahasa Prancis) yang artinya "Kota Kecil Tiongkok". Alasan Azis menamai kota ini dengan La Petite Chine adalah karena kota itu jadi titik awal pendaratan orang-orang Tiongkok di tanah Jawa, ketika rombongan ekspedisi Laksamana Cheng Ho tiba pada 1413.
Salah satu awaknya kapal bernama Bi Nang Un memilih untuk tetap tinggal di sana. Ia lalu pulang untuk membawa anak dan istrinya sambil membawa benda-benda dari Champa. Sejak itu komunitas Tionghoa berkembang pesat.
Menurut M Abi Kurniawan dalam buku Aktivitas Ekonomi Tionghoa di Lasem Tahun 1945-1950, orang Tionghoa yang bermukim di Lasem adalah suku bangsa Hokka yang berasal dari Provinsi Guangdong di Tiongkok selatan.
Orang Hokka diketahui senang merantau ke daerah selatan yang lebih hangat dari tempat tinggal aslinya. Namun demikian suku Tie Ciu dan Kwang Fu yang berasal dari pesisir pantai utara Tiongkok atau tepatnya pedalaman Swatow di bagian timur Provinsi Kwantung, juga turut datang dan berdiam di Lasem.
Namun sebelum kedatangan orang Tiongkok, Lasem sudah menjadi kota yang maju. Kota kecil di pesisir Jawa ini sempat disebut dalam Serat Badra Santi yang ditulis Mpu Santi Badra pada tahun 1479. Disebutkan bahwa pada 1273 Saka atau 1351 Masehi, Lasem telah menjadi tanah perdikan Majapahit.
Lasem disebut kota pantai yang menjadi pusat pembuatan kapal. Peter Boomgaard dalam bukunya, Children of the Colonial State: Population Growth and Economic Development in Java, 1795-1880 (1989) menyatakan, sebelum kedatangan Belanda, Lasem dan Rembang telah menjadi pusat pembuatan kapal dan ada sekitar 500 orang yang bekerja di bidang ini.
Sementara itu dalam buku Suma Oriental que Trata do Mar Roxo até aos Chins (Ikhtisar Wilayah Timur, dari Laut Merah hingga Negeri Tiongkok) yang ditulis Tomé Pires pada 1512-1515, mencatat Lasem, yang waktu itu masuk dalam wilayah kekuasaan Brhe Lasem, sejak dahulu mempunyai galangan kapal.
Interaksi orang Jawa dan Tionghoa terbangun terutama dalam hal transaksi jual-beli. Bagi orang Jawa, orang Tionghoa dikenal ulet dan terampil, sehingga mereka banyak berguru dan meniru. Jejak akulturasi itu dapat dilihat pada kain batik dan juga bangunan yang ada.
Kelenteng Cu An Kiong merupakan salah satu yang dipercaya sebagai kelenteng tertua di Jawa. Menurut catatan di sebuah museum di Den Haag, Belanda, kelenteng ini dibangun pada 1477.
Beralamat di Jalan Dasun, Nomor 19, Pereng, Soditan, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, namanya memiliki arti Istana Kebajikan dan Kedamaian atau Ci An Gong.
Saat memasuki pintu gerbang wisatawan akan disambut dengan ornamen naga. Interior dindingnya dipenuhi lukisan tentang dewa-dewi. Kelenteng Cu An Kiong adalah kelenteng tertua dengan dewa utamanya adalah Dewi Samudra.
Bangunannya menggunakan material kayu jati yang tersedia melimpah. Tiang penyangga utama kelenteng ini merupakan dua buah kayu jati yang belum pernah diganti hingga sekarang. Klenteng ini sekaligus menjadi saksi perkembangan Kota Lasem yang semakin hari semakin ramai.
Kelenteng pernah dipugar dengan mendatangkan para ahli ukir dari Guangdong. Para ahli ukir tersebut akhirnya menetap di Kabupaten Kudus dan mengajar penduduk setempat. Salah satu ahli ukir terkenal adalah Tiang Sun Khing. Namanya kemudian diabadikan menjadi nama desa yaitu Sunggingan. Sementara itu, ahli ukir lainnya yaitu Tee Ling Sing lebih dikenal dengan nama Kyai Telingsing.
Pada 1838 bangunan direnovasi dengan meninggikan lantai bangunan. Hal ini karena tempat tersebut sering mengalami banjir karena lokasinya tepat berada di depan Sungai Lasem. Sungai ini dulu sebagai sarana lalu lintas kapal dengan dermaga kapal meski kini tidak berbekas.
Sementara itu Kelenteng Gie Yong Bio merupakan salah satu tempat peribadatan umat Tridharma. Kelenteng ini memiliki keistimewaan karena dibangun untuk menghormati tiga pahlawan Lasem yaitu Tan Kee Wie, Oey Ing Kiat, dan Raden Panji Margono.
Kelenteng ini dianggap sebagai satu-satunya kelenteng di Indonesia yang memiliki kongco (kakek buyut) pribumi untuk menghormati Raden Panji Margono sebagai dewa oleh komunitas Tionghoa di Lasem dan fakta ini amat unik karena menjadi bukti persahabatan leluhur kedua komunitas.
Sejarahnya terjadi pada 1740, saat masyarakat Tionghoa di Batavia melakukan pemberontakan melawan pemerintahan Belanda. Pemberontakan etnis tersebut mempengaruhi hampir seluruh Pulau Jawa dan Kota Lasem menjadi basis terakhir pemberontakan. Pada peristiwa itu, etnis Jawa dan Tionghoa bekerja sama.
Raden Panji Margono, putra Tejakusuma V yang menjabat sebagai Adipati Lasem (1714-1727), mengikat tali persaudaraan dengan Mayor Oei Ing Kiat. Keduanya juga mengangkat sumpah persaudaraan dengan Tan Kee Wie, seorang pengusaha serta ahli kungfu di Lasem.
Pada saat terjadi pengungsian besar-besaran etnis Tionghoa dari Batavia pada tahun 1741, ketiganya sepakat untuk mengangkat senjata memberontak terhadap VOC, meski akhirnya kalah. Pada 1750, Raden Panji Margono, Mayor Oei Ing Kiat, bersama Kyai Ali Badawi kembali mengobarkan peperangan dengan Belanda namun kalah lagi.
Dalam pertempuran itu Panji Margono gugur di Karangpace Narukan, sementara Oei Ing Kiat gugur di Layur, Lasem utara.
Untuk menghargai jasa-jasa kepahlawanan Tan Kee Wie, Panji Margono, dan Oei Ing Kiat, masyarakat Tionghoa di Lasem membangun kelenteng Gie Yong Bio sebagai monumen peringatan ketiganya.
Ketiganya dihormati sebagai kongco dan dibuat rupangnya untuk diletakkan di atas altar. Rupang Oey Ing Kiat dan Tan Kee Wie diletakkan berdampingan dan disebut dengan nama Tan Oei Ji Sian Seng (menurut dialek Hokkien), sementara rupang Raden Panji Margono diletakkan pada altar khusus yang terpisah.
Peninggalan Bangunan
Bangunan bercorak arsitektur Tionghoa selanjutnya adalah Rumah Oei. Bangunan ini berupa gerbang kuno dengan daun pintu dua lapis berwarna coklat tua berukir huruf Tiongkok keemasan. Bangunan ini cukup menonjol dibandingkan dengan bangunan di sekitarnya.
Terletak di Jalan Jatirogo, Desa Karangturi, Lasem, nama Rumah Oei yang tertera pada sebuah papan di atas gerbang tersebut. Saat ini bangunan ini menjadi pusat seni, budaya, dan kuliner di Lasem. Di dalamnya terdapat kursi besi kuno dengan meja bertaplak yang ditata berhadap-hadapan.
Difungsikan sebagai kafe, Rumah Oei menyediakan beragam kuliner khas Lasem seperti Soto Kemiri, Kelo Mrico, Oseng Nus Ireng, dan lainnya. Di tengah halaman rumah ini tumbuh pohon mangga besar yang daunnya membuat seluruh halaman terlindung sinar matahari.
Dalam sejarahnya, Rumah Oei dibangun oleh Oei Am yang merantau dari Tiongkok ke pesisir Lasem saat usianya 15 tahun. Pada usia 17 tahun ia menikah dengan seorang perempuan Lasem tulen yang kemudian dinamai Tjioe Nio. Nama ini menggambarkan seorang yang pandai menari dan membatik.
Bersama istrinya inilah, Oei Am pada 1818 membangun rumah tersebut. Bangunannya yang megah namun sederhana ini mengadopsi ciri bangunan yang ada di Tiongkok pada abad 17-18-an. Di sebuah sudut rumah ini terpajang primbon Jawa dan shio Tiongkok. Terdapat juga syair Joyoboyo yang bersama terjemahan dalam bahasa Mandarin dan Inggris.
Jejak bangunan masa lalu di Lasem selanjutnya adalah Lawang Ombo yang artinya pintu luas. Rumah ini diperkirakan dibangun pada akhir abad ke-18, dengan pemilik seorang pejabat rendah asal Tiongkok yang bergelar dengshilang bernama Lim Cui Soon. Makam atau bong Lim Cui Soon berada di samping rumah ini.
Lawang Ombo memiliki arsitektur Tiongkok dengan atap bergaya ekor walet, yang merupakan lambang kesejahteraan. Sesuai namanya kusen pintu utamanya sangat besar dengan lebar sekitar tiga meter dan tinggi 2,5 meter.
Ukuran kusen pintu dan jendelanya yang lebar menjadi menjadi daya tarik di sudut-sudut bangunan Pecinan Lasem Gambiran, Babagan, dan Karangturi. Tempat ini semakin menarik karena Lawang Ombo bertetangga dengan kelenteng tua Cu An Kiong. hay/I-1
Akulturasi Budaya dalam Sepotong Kain
Keberadaan orang-orang Tionghoa berpengaruh pada hasil kerajinan kain batik. Di beberapa sentra batik di kota itu bisa dijumpai motif-motif yang berasal dari pengaruh budaya Tionghoa seperti motif burung Hong (lok can), naga, Kilin, ayam hutan dan sebagainya.
Namun demikian tidak semuanya batik di Lasem saat ini dipengaruhi oleh budaya Tionghoa. Beberapa motif non-Tionghoa adalah motif Sekar Jagad, Kendoro Kendiri, Grinsing, Kricak atau Watu Pecah, Pasiran dan lainnya.
Produk batik Lasem dapat dijumpai di Desa Babagan yang kini jadi tujuan wisata batik di Kota Pusaka Lasem. Tempat yang sejak 2015 menjadi desa wisata ini, berdekatan dengan tempat wisata sejarah bangunan masyarakat Tionghoa seperti Kelenteng Gie Yong Bio.
Objek kunjungan lainnya adalah Wisata Jembatan Gandul dan Wisata Makam Kuno.
Tidak sulit mencari lokasi Desa Babagan karena saat memasuki wilayah Lasem, sebuah gapura berdiri kokoh dengan bertuliskan "Selamat Datang di Desa Wisata Babagan". Tak jauh dari gerbang desa wisata, terdapat galeri pemasaran produk batik Lasem.
Ciri khas batik Lasem adalah proses pembuatannya yaitu batik tulis. Berbeda dengan daerah lain, di Lasem, pembeli tidak akan menemukan batik cap apalagi printing. Untuk melihat proses pembuatan batik, para pengunjung dapat masuk ke wilayah desa mengikuti jalan utama serta memilih pembatik yang namanya tertera pada penunjuk jalan yang berada di sepanjang jalan.
Di Babagan kita bisa belajar membatik dari para pengrajin. Bahkan jika ingin menginap, tersedia homestay di rumah warga maupun pengrajin batik dengan biaya mulai 100.000 rupiah per malam. Selain belajar membatik, kelenteng dan rumah bergaya arsitektur Tionghoa juga menjadi daya tarik wisata di Desa Babagan.
Untuk menghasilkan satu batik tulis Lasem perlu waktu relatif lama. Sementara untuk menghasilkan satu helai batik tulis 1 warna dibutuhkan waktu 1 hari. Sedangkan untuk menghasilkan batik tulis klasik karya warna dibutuhkan waktu berminggu-minggu.
Secara teori menurut Kusnin Asa dalam buku Mosaic of Indonesia Batik, batik Lasem masuk dalam kategori batik pesisir, bukan golongan batik pedalaman atau batik keraton. Ciri khasnya memiliki warna-warna beragam dan cenderung cerah.
Menurut buku sejarah batik Lasem berjudul Batik: Warisan Adiluhung Nusantara karangan Musman Asti dan Ambar B Arini, batik Lasem merupakan salah satu jenis batik pesisiran yang memiliki ciri khas tersendiri. Kekhasan tersebut merupakan hasil dari akulturasi dari budaya Tiongkok dan Jawa.
Sebelum kedatangan orang Tiongkok, batik Lasem telah berkembang pada masa pemerintahan Bhre Lasem I (1350-1375). Dalam buku Akulturasi Lintas Zaman di Lasem: Perspektif Sejarah dan Budaya (2015), Nurhajarini menerangkan bahwa pada masa itu batik sudah menjadi pakaian bangsawan di wilayah Lasem.
Kemudian batik Lasem berkembang dengan kedatangan ekspedisi di bawah pimpinan Laksamana Cheng Ho, yang diutus oleh pemerintahan Dinasti Ming. Kapal mereka berlabuh di dekat Lasem pada 1413 M. Menurut sejarawan R Panji Kamzah dalam Carita Sejarah Lasem, salah seorang anggota armada bernama Bi Nang Un tertarik untuk menetap di Lasem.
Atas izin Cheng Ho, Bi Nang Un pulang ke Champa untuk menjemput keluarganya dan kembali ke Lasem bersama istri, anak, dan kerabat. Mereka kemudian tinggal di rumah yang saat ini berada di Desa Jolotundo. Rumah itu hadiah dari Adipati Lasem Wijayabadra.
Anaknya yang bernama Bi Nang Ti kemudian hari menikah dengan Adipati Badranala. Ia mengajari penduduk dengan kreasi batik bermotif Tiongkok, di samping mempelajari motif-motif yang terinspirasi benda-benda, tumbuhan dan hewan lokal. Dari sini titik awal akulturasi budaya khususnya batik terjadi.
Ketika Belanda datang ke Lasem, mereka mengikuti jejak pedagang Portugis dan mengembangkan wilayah perdagangan batik untuk pasar mancanegara seperti Singapura dan Srilanka. Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Daendels, rakyat Lasem juga dipaksa untuk membangun Jalan Raya Anyer-Panarukan.
Dari kejadian-kejadian yang terjadi saat terjadi kerja paksa tersebut tercipta motif Krecak atau Watu Pecah. Motif batik Lasem kini terus berkembang dengan motif yang terus bertambah. Hal ini menjadi gambaran nyata dinamisnya kehidupan di Lasem. hay/I-1
Redaktur : Ilham Sudrajat

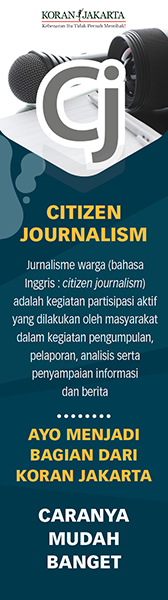

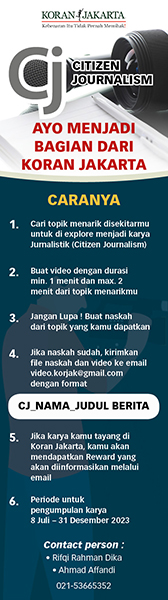
Komentar
()Muat lainnya